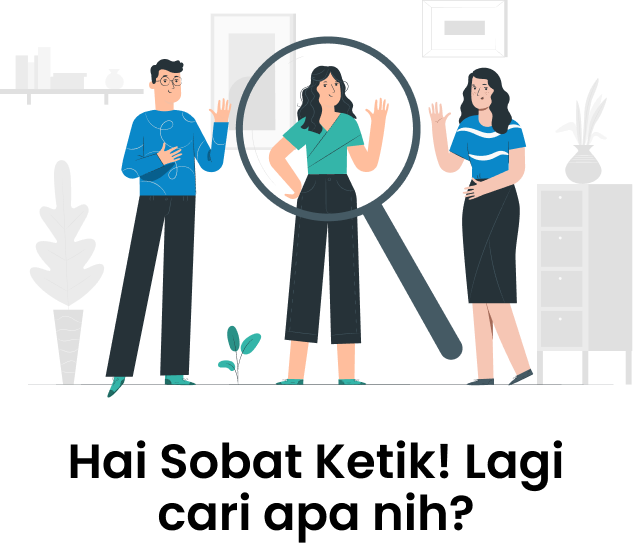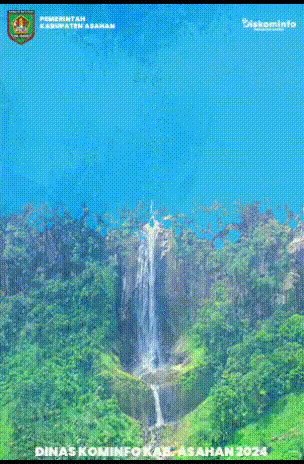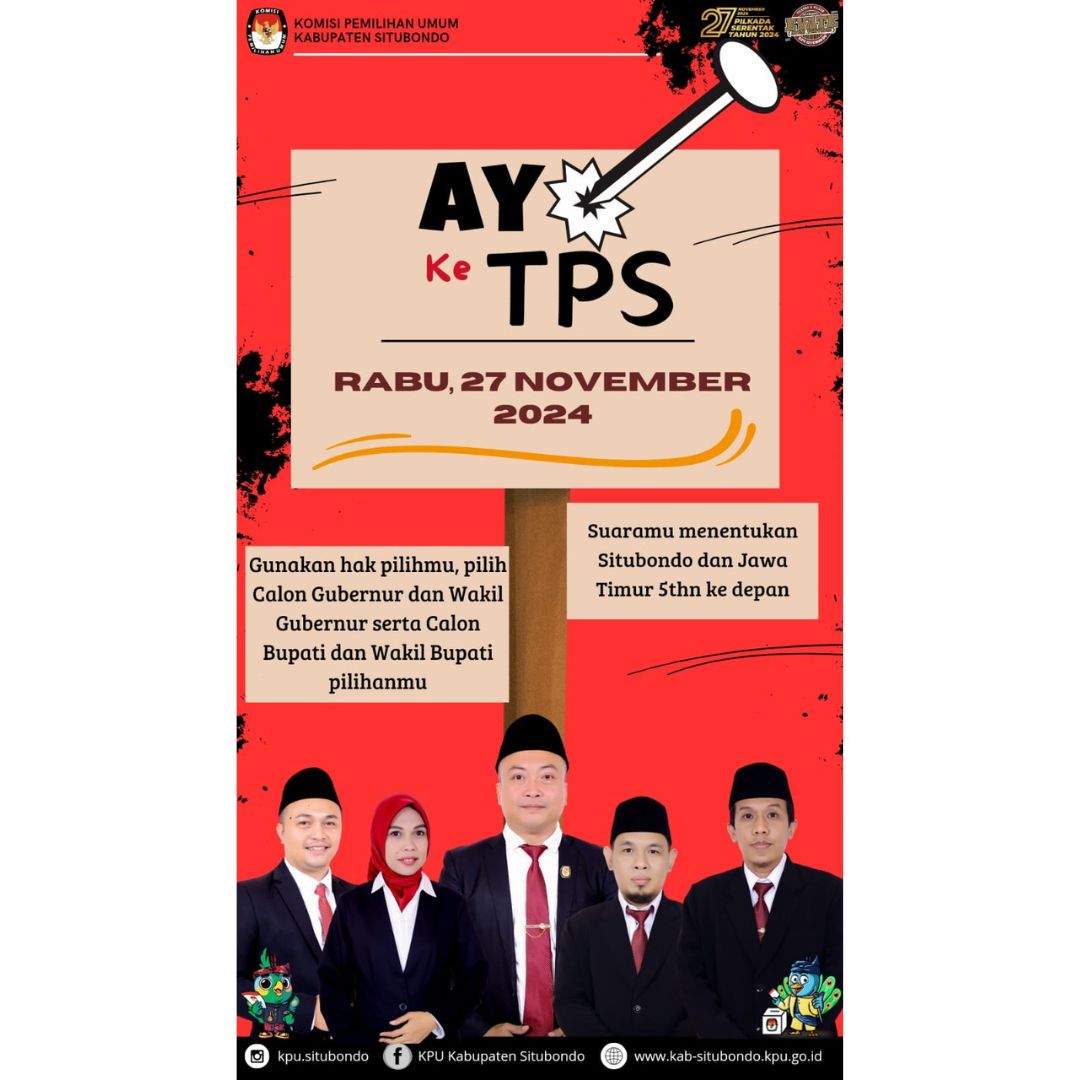KETIK, PACITAN – Upacara adat Tetaken di Pacitan, memiliki sejarah panjang dan sejumlah fakta unik. Tradisi ini terkait dengan prosesi sakral purnawiyata murid Mbah Tunggul Wulung usai berhasil menyelesaikan pertapaannya di Gunung Limo (lima), Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
Tradisi tersebut telah ada sejak ratusan tahun lalu, dan kini dapat dinikmati masyarakat luas, digambarkan melalui upacara adat yang disebut Tetaken.
Ritual yang kental dengan suasana mistis religius itu rutin digelar setiap tanggal 1 Suro (Muharam), disusul upacaranya dilakukan tanggal 15 Suro. Bahkan, pada tahun 2020 lalu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud RI, dengan nomor registrasi 202001176.
Secara turun-temurun, upacara tersebut menceritakan tentang purnanya (wisudanya) para pertapa dalam menuntut ilmu di Padepokan Tunggul Wulung. Atas keberhasilan itu, kemudian disambut rasa syukur oleh keluarga dan warga setempat.
Wujud rasa syukurnya, berupa gelaran tasyakuran oleh masyarakat di Pelataran Gunung Limo. Hingga kemudian hal tersebut ditradisikan turun temurun guna mengingat kembali proses datangnya Eyang Tunggul Wulung, terlebih singgahnya di lereng Gunung Limo pada saat itu.
 Putra Mantu Juru Kunci Pertama Gunung Limo Somo Sogimon Karsodikromo, yang rumahnya digunakan untuk sarasehan cikal bakal padepokan Resi Tunggul Wulung Tetaken. Bernama Mbah Haji Saeko yang juga selaku Penerus Kasepuhan Padepokan Karsodikromo Somodogimon, Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Pacitan. ( Foto: Al Ahmadi/Ketik.co.id)
Putra Mantu Juru Kunci Pertama Gunung Limo Somo Sogimon Karsodikromo, yang rumahnya digunakan untuk sarasehan cikal bakal padepokan Resi Tunggul Wulung Tetaken. Bernama Mbah Haji Saeko yang juga selaku Penerus Kasepuhan Padepokan Karsodikromo Somodogimon, Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Pacitan. ( Foto: Al Ahmadi/Ketik.co.id)
Sejarah Panjang Upacara Adat Tetaken
Diceritakan oleh Putra Mantu Juru Kunci Pertama Gunung Limo Somo Sogimon Karsodikromo, yang rumahnya digunakan untuk sarasehan cikal bakal padepokan Resi Tunggul Wulung Tetaken.
Bernama Mbah Haji Saeko yang juga selaku Penerus Kasepuhan Padepokan Karsodikromo Somodogimon, Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Pacitan.
Haji Saeko menceritakan, konon sejak era Brawijaya satu hingga lima daratan jawa masih belum terjamah agama Islam. Masyarakat umumnya masih memeluk ajaran Kapitayan, yang dalam peribadatannya sangat mirip dengan muslim.
"Di Jawa sudah ada (agama), tapi solatnya hanya pagi dan sore ya, persis solatnya sama islam," ucapnya.
Kemudian, kata Saeko, seorang ulama besar bernama Syek Subakir, yang mempunyai peranan sangat besar dalam membangun peradaban manusia di Pulau Jawa dan sebagai kunci masuknya ajaran agama Islam di tanah Jawa. Subakir mencoba untuk menyebarkan agama Islam ke indonesia melalui perdagangan rempah-rempah.
Kendati tak semudah itu, lanjut Saeko, dalam perjalanannya, Subakir mengalami hambatan dikarenakan adanya bangsa jin yang menempati hampir seluruh sudut pulau Jawa. Bangsa jin itu, dipimpin oleh Sabdo Palon atau juga dikenal dengan Eyang Semar, yang bersemayam di Puncak Gunung Tidar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
"Beberapa ulama melakukan penyebaran agama ke indonesia melalui perdagangan rempah-rempah," ceritanya.
Akibatnya, tambah Saeko, Subakir harus melakukan pembersihan makhluk tak kasat mata pun membuat jin diseluruh jawa bergejolak kepanasan. Bahkan, melarikan diri hingga ke lautan maupun mengungsi ke dasar gunung.
Selain menyebabkan rombongan Jin kocar-kacir, kericuhan tersebut menyebabkan Sabda Palon(Eyang Semar) yang telah bersemayam hampir 1.000 tahun keluar ke permukaan dalam wujud manusia. Tidak lain, yakni untuk bertarung dengan ulama besar itu. Mereka terlibat adu kesaktian, terjadi selama 40 hari 40 malam.
"Mereka itukan sama saktinya, dari Timur Tengah Syeh Subakir dan Sabdo Palon atau Eyang Semar dari Jawa kemudian tanding adu kesaktian (perang) selama 40 hari 40 malam, atau disebut (sampyuk)," ungkapnya.
Saeko menambahkan, ternyata Sabdo Palon kewalahan menghadapi ulama Islam itu, hingga terpaksa harus mengajak Syek Subakir membuat kesepakatan dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Sebagaian besar masyarakat meyakini, terdapat empat persyaratan yang akhirnya disepakati, salah satunya tidak diperkenankan untuk merubah adat ketimuran (Jawa) menyerupai bangsa Arab.
Bermula dari hal itu, lanjut Saeko, cikal bakal penyebaran Agama Islam di tanah Jawa mulai ada titik terang, pun membuat beberapa ulama mendakwahkan Islam menggunakan kearifan lokal guna tetap menjaga budaya yang telah ada.
"Melalui perjanjian di pusere (tengah-tengah) tanah Jawa yaitu Gunung Tidar yang sekarang untuk pendidikan tentara," kisahnya.
Saeko melanjutkan, sekitar 15 tahun perjanjian itu disepakati, dan telah dilakukan penyebaran agama Islam melalui Walisongo. Berangsur-angsur terjadi peralihan zaman, dari Hindu-Buddha ke Islam, hingga runtuhnya Majapahit menuju kejayaan Mataram Islam.
Pada masa itu Eyang Tunggul Wulung merupakan abdi dalem (orang yang mengabdikan dirinya kepada keraton) sebagai penjaga kerajaan Majapahit. Terdiri dari Eyang Lawu dan Eyang Tunggul Wulung.
"Eyang Resi Tunggul Wulung adalah penjaga kerajaan Majapahit tanah jawa," tambahnya.
Disusul kabar pilu muksonya Raja Majapahit Prabu Brawijaya V (pada saat itu juga berhasil di Islamkan oleh Sunan Kalijaga) di Gunung Lawu. Eyang Tunggul Wulung yang sebagai penjaga pusaka kerajaan tidak menerima hal tersebut.
"Kemudian Tunggul Wulung pergi menenangkan diri jalan ke selatan (ke Pacitan), sedangkan Eyang Lawu tetap di Gunung Lawu," ungkapnya.
Seiring waktu berjalan, cerita Saekk, Resi Tunggul Wulung memutuskan untuk menenangkan diri menetap di Lereng Gunung Limo, yang malah menorehkan banyak kebajikan. Salah satunya mendirikan padepokan hingga mendidik para pertapa yang jadi asal usul Upacara Adat 'Tetaken" di Pacitan.
Lanjutnya, Tunggul Wulung pada saat itu masih menganut ajaran Kapitayan dan cukup lama telah menghuni wilayah tersebut. Walisongo sudah bergerilya dalam upaya Islamisasi ke berbagai wilayah daratan Jawa.
Di samping itu juga menyasar wilayah selatan, termasuk wilayah Resi Tunggul Wulung yang menghuni Lereng Gunung Limo.
Saeko meneruskan ceritanya, tidak diketahui percekcokan apa telah terjadi pada saat itu, para Walisongo kemudian berhasil mengajak Tunggul Wulung bersyahadat dan memeluk agama Islam.
Hingga akhirnya dari kisah tersebut, masyarakat setempat meyakini kedatangan para Walisongo, dan dapat dibuktikan melalui adanya gerbang masuk (batu besar) di jalan pendakian kepuncak Gunung Limo.
"Gunung limo ini membuktikankan bahwa sebelum masuk islam, para wali kan mensahadatkan orang tanah Jawa. Dia(Tunggul Wulung) belum masuk islam, kemudian waktu setelah masuk Islam, kesaktian para wali itu dibuktikan dengan adanya batu besar, yang apabila membaca syahadat gerbangnya langsung terbuka," jelasnya.
Fakta Unik Gunung Limo, Gerbang Wahyu Setangkep dan Tempat Muksonya Tunggul Wulung
Tak bisa dinalar, lanjut Mbah Saeko, pasalnya pintu masuk (gerbang) pertapaan atau jalan menuju puncak sedalam tujuh meter itu, hanya memilik lebar 23 centimeter. Namun, bagi seseorang yang memang diterima (memiliki kesucian), bakal tetap muat melewati gerbang.
"Pintu itu namanya Wahyu Setangkep, kalau orang besar maupun kecil masuk dan diterima ya tetep bisa, kalau nggak diterima ya nggak bisa," jelasnya lagi.
Diyakini lagi, setelah tujuh meter masuk ke dalam, merupakan pertapaan pun sebagai tempat moksanya (membebaskan dirinya dari keterikatan dunia), Resi Tunggul Wulung.
"Lalu Gunung Limo diartikan ayo bersama sama sembahyang lima waktu, nah disitu kadang-kadang versinya ada yang lain," ucapnya.
Namun, di pertapaan juga dijelaskan terbagi menjadi dua, yakni tempat Tunggul Wulung dan Nyai Abang. Tempat yang kedua, itu merupakan jalan menuju perbuatan ingkar kepada Allah SWT.
"Yang pertapaan Nyai, itu untuk arah garis kiri lah atau jalan yang untuk perbuatan-perbuatan yang menyimpang," katanya.
Sebagaimana cerita di Desa Mantren itu. Masyarakat setempat meyakini, bahwa Kyai Tunggul Wulung merupakan tokoh Islam babad alas di wilayah tersebut, pun menorehkan berbagai kebaikan yang patut di teladan bagi sebagian besar anak cucu mereka.
"Jadi eyang tunggul wulung itu penyebar agama Islam yang sebenarnya," pungkasnya.
Rangkaian Prosesi Upacara Adat Tetaken di Desa Mantren
Dilanjutkan kembali oleh Mbah Saeko, dalam upacara adat Tetaken dimulai ketika thontongan (kentongan), dibunyikan guna menyambut sang juru kunci Gunung Lima turun dari gunung bersama para muridnya. Mereka digambarkan tengah usai bertapa di puncak gunung dan kembali ke desa.
Penyambutan itu berupa iring-iringan oleh masyarakat hingga sampai di Pelataran (depan Padepokan Gunung Limo). Barisan paling depan, terlihat membawa perlengkapan ritual, yang terdiri dari Panji Tunggul Wulung, Keris Hanacaraka, Tombak Kyai Slamet, dan Kotang Ontokusumo (Jubah Hitam pertapa).
Usai itu, selanjutnya, juru kunci menuju pelataran untuk melaksanakan prosesi nyuceni murid atau membersihkan diri secara simbolik sebagai perwujudan murid yang suci karena telah penggodokan keilmuan tentang hubungan manusia dengan alam.
Tampak, prosesi Nyuceni atau menyucikan murid terdiri dari tiga tahapan. Pertama, ikat kepala para murid dilepas sebagai tanda kelulusan. Kedua, satu persatu siswa diberi minum air sari aren yang biasa disebut sajeng. Terakhir, para murid menghadapi tes mental dengan penguasaan ilmu bela diri.
Setelah rangkaian prosesi menyucikan diri, juru kunci memberikan wejangan kepada para murid bahwa tantangan bagi pembawa ajaran kebaikan tidak ringan, banyak ujian dan rintangan berat yang harus dihadapi dalam realitas kehidupan.
Seluruh proses menyucikan diri para murid serta pemberian wejangan oleh juru kunci disaksikan oleh Demang dan seluruh masyarakat Desa Mantren yang hadir dalam upacara Tetaken.
Kemudian, murid yang telah diwisuda diserahkan kepada masyarakat Mantren. Penerimaan murid dari juru kunci Gunung Limo, Demang Mantren menerima dengan ucapan hamdalah dan bacaan Al Fatihah sebagai rasa syukur karena para murid telah melalui proses pendidikan bertapa di Gunung Limo.
Kemudian, disusul dengan penyambutan lainnya. Saat upacara berlangsung, pelaku budaya atau peserta tampak mengenakan pakaian adat Jawa laiknya masyarakat jaman dulu.
Harapannya, murid dapat membaur dengan masyarakat Desa Mantren sehingga dapat mewujudkan desa yang aman, makmur, sejahtera, dan hidup berdampingan dengan alam sekitar. Kegiatan kemudian diakhiri dengan makan bersama-sama. (*)