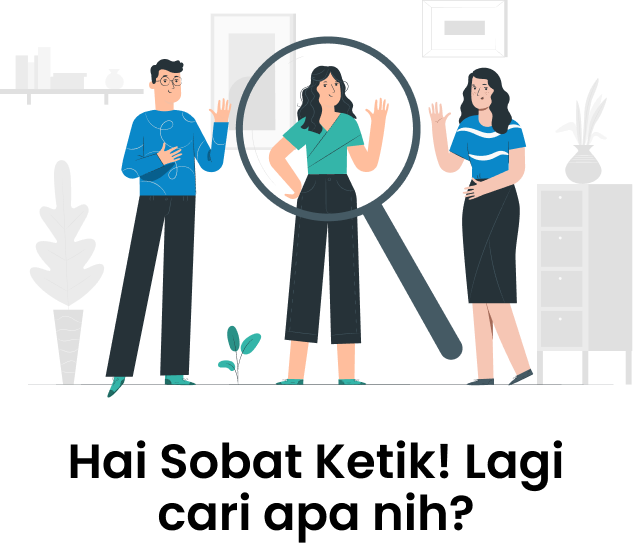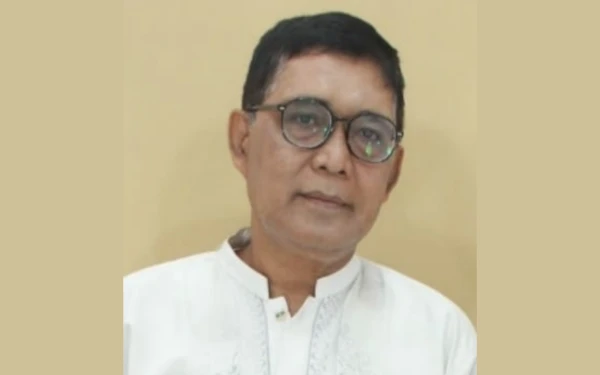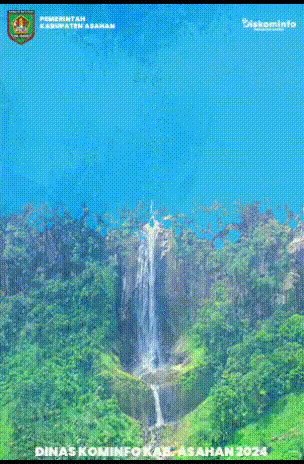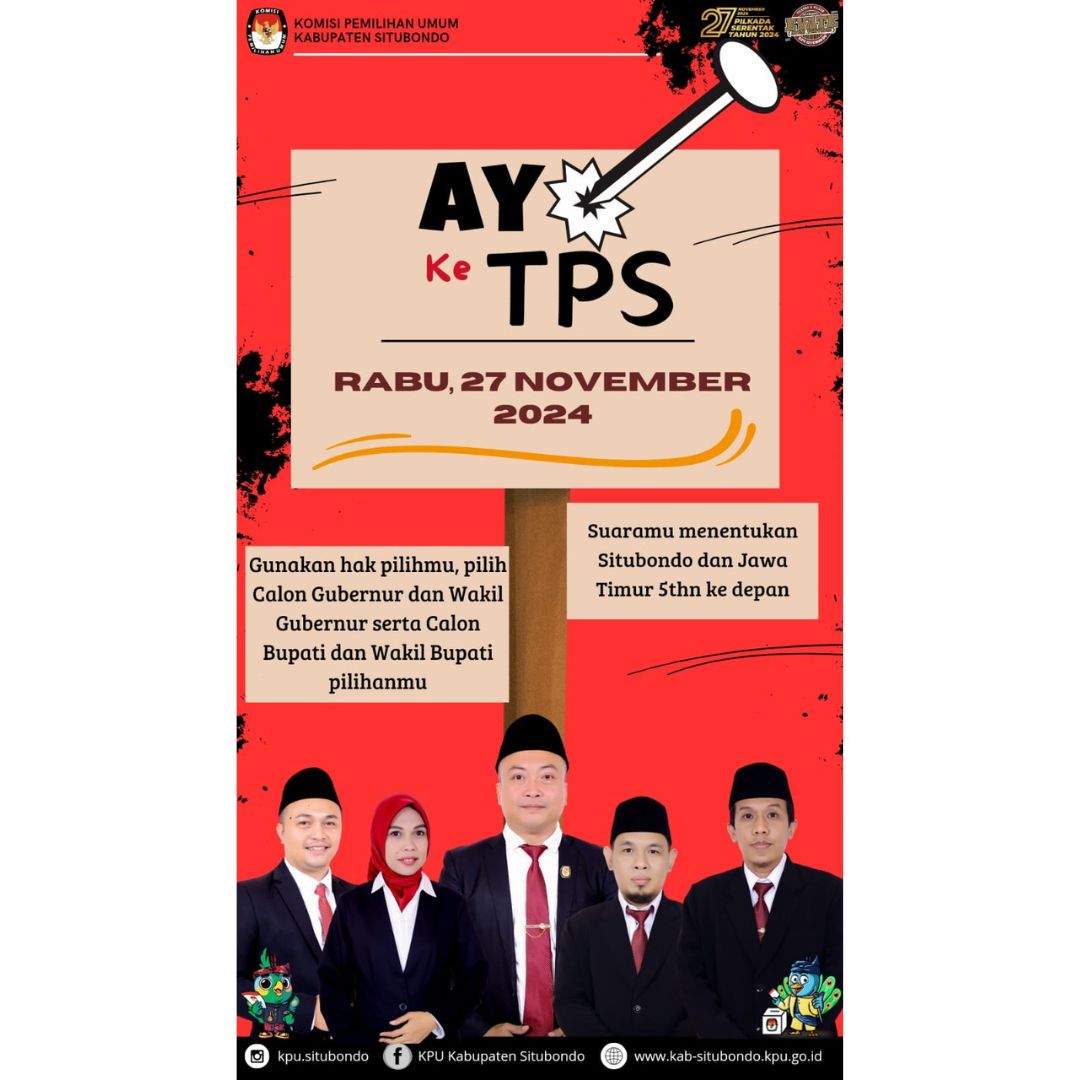KETIK, JAKARTA – Ada jagoan spin yang membela skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia tanpa mengerti soal financial dan frauds.
Demikian tulis Rizal Ramli di akun Twitter milik pribadi pada 23 Maret 2023 kemarin. Publik terhenyak bukan hanya soal skandal. Tapi apakah spin doctor itu?
Pengamat politik internasional, Tulus Sugiharto menjabarkan istilah spin doctor telah dikenal saat era Perang Dunia ke II atau PD II.
Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1980-1988 merupakan seorang perwira militer.
Ronald Reagan ingin menjadi bagian angkatan bersenjata AS berperang ke Eropa dan Asia. Akan tetapi, Mayor Ronald Reagan tidak bisa pergi ke medan perang karena memiliki penyakit rabun jauh.
Sehingga akhirnya ia hanya ditempatkan sebagai pengisi suara untuk pelatihan militer selama Perang Dunia II berlangsung.
Reagan memulai kariernya sebagai seorang penyiar radio dan kemudian menjadi aktor. Reagan sendiri memiliki ketertarikan pada bidang politik dan ia juga dikenal sebagai aktor yang anti pada gerakan komunisme.
Salah satu film berjudul Trumbo (2015) mengungkapkan bagaimana industri film Amerika diduga disusupi komunisme sesudah PD II dan masuk ke era perang dingin.
"Dulu Reagan hanya dikenal sebagai aktor kelas dua. Tapi dia memiliki insting politik yang tinggi, penampilannya yang menarik di layar TV dan film dan dia dekat dengan media, orang-orang public relations banyak anti komunis," terang Tulus Sugiharto, pengamat politik sekaligus sahabat Rizal Ramli, Senin (27/3/2023).
Dalam Pemilu 1980, Reagan melawan incumbent Jimmy Carter. Jim sebenarnya memiliki prestasi baik di dalam negeri, hanya saja kasus penyanderaan di Iran selama 444 hari menyebabkan ia tercoreng.
Untuk mengalahkan Carter, Reagan bukan hanya mengandalkan kegantengan dan suara semata. Reagan secara canggih melibatkan spin doctor, yaitu kelompok orang yang ahli dalam public relations, politisi, media bahkan akademisi.
"Hal ini baru diungkap oleh New York Times tahun 1984 saat Reagan menjadi kandidat presiden untuk kedua kalinya melawan Walter Mondale," kata Tulus.
Ia menambahkan, bahwa dalam khazanah public relation yang ditulis oleh Delanur di Kompasiana pada tahun 2016, segala bentuk manipulasi dan rekayasa informasi atau upaya membohongi publik disebut dengan teknik spin. Sementara pelakunya disebut spin doctor.
Pada tahun 1984, kata Tulus, reporter di lapangan dan juga redaksi sudah mulai dimasuki oleh para spin doctor.
"Jadi spin doctor itu bisa saja para pendukung seorang kandidat presiden dan bahkan ikut setelah orang yang didukungnya menjadi pejabat," tandasnya.
Lantas efektifkah peran seorang spin doctor tersebut?
Tulus melihat peran spin doctor kala itu memang efektif jika melihat kasus Iran Contra yang melibatkan Letkol Oliver North.
Saat itu pemerintah Amerika diduga menjual senjata pada Iran dalam perangnya melawan Irak, padahal Iran dikenal sebagai musuh AS.
Selain itu, Amerika juga membantu gerilyawan Contra dalam konflik di Nikaragua. Reagan bertahan meski skandal Iran Contra ini mendapat publikasi yang luas.
"Tapi kita ngomong hari ini, saat masuk era media baru yang berbasis pada internet," ujarnya.
Publik apalagi Gen X dan Z di era digital mulai kritis, tidak percaya begitu saja dan mampu untuk mencari informasi dari berbagai sumber.
"Biasa berpikir kritis mereka akan memulai dengan question atau pertanyaan. Nah, Bung Rizal Ramli (RR) mengajak Gen X dan Z memulai dengan question. Bung RR sebagai pemikir bangsa yang out of the box mencoba membantu mereka menjawab pertanyaan Gen X dan Z sehingga lebih kritis," jelasnya.
Kendati demikian, Tulus kembali mengatakan, hari ini mungkin spin doctor tetap saja laku dan digunakan oleh tokoh-tokoh yang mau menjadi pemimpin.
"Tapi kalau penonton, pembaca dan pendengar semakin kritis di era media baru ini, maka kebenaran akan cepat terungkap," ujarnya.
Tulus melihat jika Rizal Ramli sepakat dengan ucapan Bung Karno. Demikian bunyinya : "Saya ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Saya besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan saya penyambung lidah rakyat."
"Bung RR sama dengan Bung Karno, mendengar suara rakyat bukan kata-kata si spin doctor. Keep tweet, berikan salam good bye bagi si pengguna teknik spin dan para spin doctor," kata Tulus.
Spiral Keheningan Menguat
Sementara itu, Tulus juga berbicara tentang porsi media bagi suara-suara pembawa perubahan sangat minim. Padahal jumlah media digital era ini tak terhitung.
Sedangkan orang-orang yang lahir pada Generasi X atau Gen X pada tahun 1965-1976 mengalami keterbatasan mengakses informasi.
Indonesia pada era tahun 60 sampai dengan pertengahan 80 an hanya ada satu stasiun televisi. Jika ingin hiburan lain bisa memutar kaset, mendengarkan radio internasional atau membaca koran.
Tapi jika ada sesuatu yang mengganjal pada sebuah berita atau tayangan tentang kebijakan pemerintah atau apapun, maka feedback ketidakpuasan itu hanya dalam bentuk surat pembaca. Isi media pada waktu itu slogannya bebas, tapi bertanggung jawab.
Kemudian media lebih bebas setelah TV swasta mulai muncul di akhir tahun 80 an dan awal 90 an, berita-berita mulai bebas, asal tidak menyinggung keluarga penguasa saat itu.
Pada era tahun 70an muncul spiral of silent atau teori keheningan. Teori ini diperkenalkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann di tahun 1974.
Pada tulisan Antonia Rucita (Binusian Communication) 6 Oktober 2021, disebutkan dalam penelitiannya, Noelle-Neumann menyatakan media mempengaruhi opini publik.
"Teori ini benar jika melihat kondisi media di Indonesia pada tahun 70an itu. Teori ini menganggap pengaruh penting dari media adalah pembentukan opini publik yang secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan memicu timbulnya kelompok mayoritas serta minoritas," ucap Tulus.
"Tapi saya berpendapat dalam konteks Indonesia (saat itu) , perlu dilihat soal kata mayoritas. Mayoritas di sini lebih pada konteks peran penguasa yang secara luas menguasai isu publik melalui media," ucap Tulus.
Media yang dikuasai pemerintah dan sulitnya masyarakat melakukan feedback melalui media direspon oleh Jurgen Habermas seorang pemikir Jerman, yang menjadi penerus langsung pemikiran kritis dari mazhab Frankfurt atau Frankfurter Schule.
Habermas mengatakan perlu adanya public sphere atau ruang publik untuk berdiskusi dan bersikap kritis pada sebuah masalah.
Pasca reformasi, maka ruang publik untuk mengkritisi apapun, termasuk kebijakan pemerintah mulai terbuka.
Tapi apakah di era reformasi ini, media mainstream akan bersikap independen dalam membuat sebuah konten?
"Mungkin pekerja media mainstream ingin bersikap independen atau bebas, tapi bukankah sebuah konten bisa dipengaruhi (bahkan) diintervensi oleh pemilik media, penguasa atau bahkan pengiklan," katanya.
Spiral of silent kini mulai menguat, memanfaatkan public sphere tadi dengan munculnya media baru yang berbasis pada internet.
Dulu media mainstream perlu beberapa gate keeping agar sebuah konten muncul. Tapi sekarang seorang netizen bisa membuat konten sendiri, merencanakan, membuatkan atau merekam, mengedit dan menayangkannya sendiri tanpa ada gate keeping.
Ada positif tapi ada yang konten yang kurang bagus bahkan negatif, bahkan mungkin ada buzzer pembuat konten palsu.
Tulus melihat kaum X yang dulu medianya terbatas, tapi sekarang bergabung dengan kaum gen Y dan Z yang dekat akses informasi yang bebas, mereka bisa menjadi bagian bagi public sphere yang kritis.
Bung Karno pada masa dahulu mempengaruhi massa dengan pidato-pidatonya yang sangat menggelora, membuat publik bangkit untuk merdeka.
"Bung RR kini mungkin kurang dilirik oleh media mainstream, tapi si bung muncul di macem-macem media baru seperti di YouTube. Kalau Bung Karno dulu rajin turun ke lapangan, pidato di tempat tempat terbuka, sekarang Bung RR rajin turun di tempat yang lebih terbuka di media digital," beber Tulus.
"Dan kalau public sphere mau terus kritis, spiral (not) silent, kini menjadi putaran besar, maka gen X, Y dan Z jangan sungkan ajak si Bung RR diskusi menciptakan pemikiran yang out of the box melalui media sosial twitternya," sambungnya.(*)